 Saya membantu persiapan dan peluncuran sebuah laporan Human Rights Watch soal pesakitan politik Maluku dan Papua. Saya suka laporan ini. Ia menyajikan profile 10 narapidana politik dari wawancara lebih dari 50 pesakitan di berbagai penjara di Papua, Pulau Ambon dan Pulau Jawa. Judulnya, Prosecuting Political Aspiration: Indonesia's Political Prisoners. Human Rights Watch juga menterjemahkan ke Melayu Indonesia dengan judul Kriminalisasi Aspirasi Politik: Pesakitan Politik di Indonesia.
Saya membantu persiapan dan peluncuran sebuah laporan Human Rights Watch soal pesakitan politik Maluku dan Papua. Saya suka laporan ini. Ia menyajikan profile 10 narapidana politik dari wawancara lebih dari 50 pesakitan di berbagai penjara di Papua, Pulau Ambon dan Pulau Jawa. Judulnya, Prosecuting Political Aspiration: Indonesia's Political Prisoners. Human Rights Watch juga menterjemahkan ke Melayu Indonesia dengan judul Kriminalisasi Aspirasi Politik: Pesakitan Politik di Indonesia.Mereka dipenjara, paling tinggi 20 tahun, karena kegiatan politik. Kebanyakan terkait dengan penaikan bendera Bintang Kejora atau Republik Maluku Selatan. Mereka tak melakukan kekerasan. Para pesakitan Alifuru termasuk sekelompok lelaki yang menarikan cakalele di Stadion Ambon, 29 Juni 2007, di hadapan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
 Phil Robertson dari Human Rights Watch serta Johnson Panjaitan dari Tim Advokasi Masyarakat Sipil Maluku bicara pada peluncuran di Hotel Grand Cemara, 23 Juni 2010. Haris Azhar dari Kontras juga ikut minta pemerintah Indonesia membebaskan para pesakitan itu. ©2010 Andreas Harsono
Phil Robertson dari Human Rights Watch serta Johnson Panjaitan dari Tim Advokasi Masyarakat Sipil Maluku bicara pada peluncuran di Hotel Grand Cemara, 23 Juni 2010. Haris Azhar dari Kontras juga ikut minta pemerintah Indonesia membebaskan para pesakitan itu. ©2010 Andreas HarsonoHuman Rights Watch tak punya posisi dalam isu self-determination di Indonesia. Laporan ini juga tidak bermaksud sebagai bentuk dukungan atau pun pelecehan terhadap aspirasi merdeka dari aktivis Papua maupun Alifuru. Namun konsisten dengan hukum internasional, Human Rights Watch mendukung hak semua orang, termasuk pendukung self-determination, untuk mengungkapkan pandangan politik mereka secara damai, tanpa ketakutan atau ditangkap atau menerima hukuman.
Sebagian besar dari pesakitan politik ini divonis makar dengan pasal 106 dan 110 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Dalam beberapa kasus, mereka disiksa di tahanan maupun penjara. Beberapa menerima penganiayaan serta penolakan bantuan medis selagi di penjara.
 Enam orang pesakitan politik Maluku di penjara Lowokwaru, Malang. Berdiri (kiri ke kanan): Yunus Maryo Litiloly, Johan Teterisa dan John Syaranamual. Duduk: Leonard Joni Sinay, Leonard Hendriks dan Ferjohn Saiya. Johan Teterisa, seorang guru SD di desa Aboru, Pulau Haruku, memimpin 27 penari membawakan tarian cakalele sambil mengibarkan bendera RMS pada 29 Juni 2010. ©2009 Abraham Hamzah
Enam orang pesakitan politik Maluku di penjara Lowokwaru, Malang. Berdiri (kiri ke kanan): Yunus Maryo Litiloly, Johan Teterisa dan John Syaranamual. Duduk: Leonard Joni Sinay, Leonard Hendriks dan Ferjohn Saiya. Johan Teterisa, seorang guru SD di desa Aboru, Pulau Haruku, memimpin 27 penari membawakan tarian cakalele sambil mengibarkan bendera RMS pada 29 Juni 2010. ©2009 Abraham Hamzah Menurut Johan Teterisa dari desa Aboru, Pulau Haruku, dia ditangkap petugas Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) saat menari cakalele di depan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan tamu lain. Hanya dalam hitungan jam, dia sudah disiksa oleh polisi Ambon di markas besar Detasemen Khusus 88, daerah Tantui, Ambon. Mereka memukul Teterisa sekitar 12 jam setiap hari selama 11 hari. Dia dipukul dengan batang besi dan batu, serta disayat dengan bayonet.
Pada 30 Juni 2007, empat polisi Detasemen Khusus 88 memukulnya di pinggir pantai, berguling-guling hingga masuk laut. Mereka terus pukul dia dalam air laut. Teterisa mengatakan dada serasa remuk, beberapa tulang rusuk patah, serta tubuh lebam-lebam hitam.
Suatu malam, Juli 2007, sekitar pukul 23:00, beberapa petugas membawa Teterisa ke Stadion Merdeka. Dia diborgol dan berjalan dengan todongan pistol. “Beta terus berdoa. Beta takut dihabiskan malam itu. Beta pikir mereka cuma punya satu pilihan: bunuh beta.” Ternyata Teterisa hanya diminta menunjukkan tempat kejadian, cerita rute masuk stadion, lalu dibawa kembali ke tahanan. Kini di penjara Lowokwaru, menjalani hukuman 15 tahun, Teterisa mengatakan sering pusing kepala dan tak bisa tidur pada sisi badan yang tulang rusuk patah.
Reimond Tuapattinaya, juga pesakitan RMS, kini di penjara Kediri dengan hukuman makar karena ikut upacara bendera RMS pada 25 April 2006, mengatakan, "Kita dibuka pakaian, tinggal celana dalam, tidur dikasih di atas tegel, pagi-pagi disuruh merayap, ditendang, diinjak. Kalau mereka pegang besi, kita kena besi. Kalau mereka pegang kayu, ya kita kena kayu. Kabel ya kabel. Sepatu, kepalan tangan." Tuapattinaya ada 14 hari di Tantui, disiksa setiap hari. "Siang diambil, sore dikembalikan ke tahanan," katanya.
Pengacara Johnson Panjaitan dari Tim Advokasi Masyarakat Sipil Maluku (Tamasu) mengatakan dia sudah bekerja selama 20 tahun mendampingi macam-macam pesakitan politik, dari Aceh hingga Papua, dari Ambon hingga Timor Timur. Dia bilang pesakitan Alifuru adalah korban siksaan paling kejam di Indonesia. Ambon juga termasuk kasus pelanggaran hak asasi manusia berat yang paling jarang dimengerti orang.
 Dalam laporan Human Rights Watch, salah satu pesakitan yang mungkin paling terkenal di Papua adalah Filep Karma. Dia ditangkap 1 Desember 2004. Pada Mei 2005, pengadilan negeri Abepura menyatakan Karma bersalah dengan tuduhan makar setelah mengorganisir aksi pro-kemerdekaan pada 1 Desember 2004, dan dihukum 15 tahun penjara. Dia telah menikah dengan seorang therapist Jawa. Mereka memiliki dua anak perempuan. Putri sulung Audryne (bergambar dengan Bapanya ©2007 Audryne Karma) kini kuliah di Jawa.
Dalam laporan Human Rights Watch, salah satu pesakitan yang mungkin paling terkenal di Papua adalah Filep Karma. Dia ditangkap 1 Desember 2004. Pada Mei 2005, pengadilan negeri Abepura menyatakan Karma bersalah dengan tuduhan makar setelah mengorganisir aksi pro-kemerdekaan pada 1 Desember 2004, dan dihukum 15 tahun penjara. Dia telah menikah dengan seorang therapist Jawa. Mereka memiliki dua anak perempuan. Putri sulung Audryne (bergambar dengan Bapanya ©2007 Audryne Karma) kini kuliah di Jawa.Karma lahir pada 1959 dari keluarga terpandang di Papua. Ayahnya, Andreas Karma, seorang birokrat berpendidikan Belanda. Selama dua periode, dia ditunjuk sebagai bupati Wamena pada 1970-an dan Serui pada 1980-an, juga dua periode. Andreas Karma total jadi bupati selama 20 tahun. Dia salah satu birokrat paling populer di Biak, Serui dan Wamena. Sepupu Filep, Constant Karma, wakil gubernur Papua. Filep Karma sendiri pernah kuliah di Universitas Sebelas Maret, Solo, serta Asian Institute of Management, Manila.
Filep Karma tak pernah menganjurkan kekerasan. Dia mengatakan, “Kami ingin membuka suatu dialog yang bermartabat dengan pemerintah Indonesia, suatu dialog antara dua orang bermartabat, dan bermartabat berarti kami tidak pakai cara-cara kekerasan.”
 Tadeus Weripang dan Simon Tuturop adalah sahabat dekat, keduanya kelahiran Fakfak, Papua, pada 1950-an. Pada 3 Juli 1982, mereka bergabung dengan puluhan warga Papua, mengibarkan bendera Bintang Kejora di Jayapura. Weripang dihukum tujuh tahun penjara sementara Tuturop 10 tahun. Kini mereka kembali dipenjara karena pengibaran bendera Bintang Kejora di Gedung Pepera di Fakfak, pada 19 Juli 2008. Pepera singkatan dari “Penentuan Pendapat Rakyat” yang disponsori PBB pada 1969. Banyak warga Papua percaya Pepera 1969 hasil manipulasi Indonesia. ©2008 Fredy Warpopor
Tadeus Weripang dan Simon Tuturop adalah sahabat dekat, keduanya kelahiran Fakfak, Papua, pada 1950-an. Pada 3 Juli 1982, mereka bergabung dengan puluhan warga Papua, mengibarkan bendera Bintang Kejora di Jayapura. Weripang dihukum tujuh tahun penjara sementara Tuturop 10 tahun. Kini mereka kembali dipenjara karena pengibaran bendera Bintang Kejora di Gedung Pepera di Fakfak, pada 19 Juli 2008. Pepera singkatan dari “Penentuan Pendapat Rakyat” yang disponsori PBB pada 1969. Banyak warga Papua percaya Pepera 1969 hasil manipulasi Indonesia. ©2008 Fredy Warpopor"Imprisoning activists for peacefully voicing their political views is an ugly stain on Indonesia's recent improvements in human rights," kata Phil Robertson dari Human Rights Watch. "It's out of step with Indonesians' growing aspirations as a democratic and rights-respecting country."
Human Rights Watch, Kontras dan Tamasu mengimbau pemerintah Indonesia segera membebaskan tanpa syarat semua pesakitan politik yang menyatakan aspirasi mereka secara damai. Pemerintah Indonesia juga harus secepatnya mencabut pasal-pasal makar KUHP maupun Peraturan Pemerintah No. 77/2007 yang melarang penggunaan bendera Acheh, Alifuru maupun Papua.
 Ferdinand Pakage bersama mamanya di penjara Abepura. Pakage dinyatakan bersalah membunuh polisi Rahman Arizona dalam sebuah demonstrasi depan kampus Universitas Cenderawasih pada 15 Maret 2006. Pakage membantah tuduhan tersebut. Dia ada di rumah saat pembunuhan. Pakage mengatakan dia disiksa, ditembak kaki kanan, dipaksa mengaku membunuh. Dia tak didampingi pengacara saat pemeriksaan polisi. Saat sidang, belakangan pengacara juga tak mengajukan saksi. Human Rights Watch mengusulkan kasus Ferdinand Pakage diperiksa ulang. Pada 22 September 2008, di penjara Abepura, tiga penjaga menyiksa Pakage. Sipir Herbert Toam memukul dengan kunci dan anak kunci menembus mata kanan Pakage. Dalam keadaan tak sadar dan berdarah, dia dilempar ke sel isolasi dan tak diobati selama 24 jam. Kini Ferdinand Pakage buta mata kanan. ©2010 Cyntia Warwe/Garda Papua
Ferdinand Pakage bersama mamanya di penjara Abepura. Pakage dinyatakan bersalah membunuh polisi Rahman Arizona dalam sebuah demonstrasi depan kampus Universitas Cenderawasih pada 15 Maret 2006. Pakage membantah tuduhan tersebut. Dia ada di rumah saat pembunuhan. Pakage mengatakan dia disiksa, ditembak kaki kanan, dipaksa mengaku membunuh. Dia tak didampingi pengacara saat pemeriksaan polisi. Saat sidang, belakangan pengacara juga tak mengajukan saksi. Human Rights Watch mengusulkan kasus Ferdinand Pakage diperiksa ulang. Pada 22 September 2008, di penjara Abepura, tiga penjaga menyiksa Pakage. Sipir Herbert Toam memukul dengan kunci dan anak kunci menembus mata kanan Pakage. Dalam keadaan tak sadar dan berdarah, dia dilempar ke sel isolasi dan tak diobati selama 24 jam. Kini Ferdinand Pakage buta mata kanan. ©2010 Cyntia Warwe/Garda Papua




1.gif)



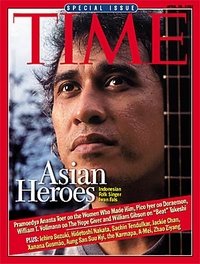








 In a bid to make sure that the bullet comes from the police, the family brought the baby to a Merauke hospital. It is already Sunday noon. The hospital obviously cannot find the bullet. It penetrated her head. Now without the bullet that killed the baby, the police claimed it will be difficult to investigate the killing. Officially they promised that they will investigate the killing. But accountability is a big question mark in Merauke. This is the same police station which denied various beatings conducted by Indonesian soldiers against Papuan youth.
In a bid to make sure that the bullet comes from the police, the family brought the baby to a Merauke hospital. It is already Sunday noon. The hospital obviously cannot find the bullet. It penetrated her head. Now without the bullet that killed the baby, the police claimed it will be difficult to investigate the killing. Officially they promised that they will investigate the killing. But accountability is a big question mark in Merauke. This is the same police station which denied various beatings conducted by Indonesian soldiers against Papuan youth.