Arya, Jadi kapan sebenarnya Pram membakar buku seperti halnya Nur Mahmudi Ismail?
Sayang sekali Anda tak bisa menjawabnya.
Saya sudah menduga Anda tak bisa menjawabnya. Saya juga bahkan sudah bisa menduga Anda akan berkelit dengan mengganti frase “Pram membakar buku” dengan frase “Pram membiarkan/menganjurkan bakar buku”. Dugaan saya sepenuhnya presisi.
(Jujur, saya tidak yakin Anda akan mengganti frase “Pram bakar buku” dengan “Pram menganjurkan/mendiamkan pembakaran” jika saya tidak menantang Anda secara terbuka untuk berbicara mengenai perkara ini secara detail – kendati Anda bilang tulisan panjang Anda bukan karena untuk menanggapi tantangan saya).
Tapi sekadar mengingatkan, tulisan Anda (baik untuk mengkritik materi pernyataan sikap, menjawab Linda atau pun menjawab Aboeprijadi) jelas-jelas menyebutkan Pram “membakari buku-buku lawan ideologisnya”.
Dan itu dilakukan berkali-kali. Terus menerus dalam tiga tulisan Anda itu (dan baru diganti dengan “membiarkan atau menganjurkan pembakaran” dalam tulisan Anda yang terbaru setelah saya menantang Anda untuk menjawabnya dengan detail).
Kita tahu semua, seperti apa kelakuan Nur Mahmudi yang pernah Anda coblos dalam perkara ini. Dengan mudah saya bisa sebutkan kapan dan di mana kelakuan Nur Mahmudi itu terjadi. Itulah sebabnya saya menantang Anda secara terbuka. Saya jengah karena Anda terus menerus menyamakan
apple to apple antara Pram dan Nur Mahmudi dalam soal bakar-membakar ini
Kita bisa berdebat soal selisih antara “membakar buku” dengan mendiamkan/menganjurkan pembakaran”. Tapi yang jelas, keduanya tidak persis.
Dengan terus-menerus mereproduksi frase “Pram membakari buku” (seperti terbaca jelas dalam 3 tulisan Anda: kritik untuk materi pernyataan sikap, jawaban pada Linda, dan jawaban pada Aboeprijadi), saya kahawatir Anda terpeleset pada “ommision of fact”. Karena Pram memang tidak membakar buku (sampai ada yang bisa membuktikannya).
Sayang bukan jika apa yang Anda sebut sebagai “memukul air di dulang terpercik wajah sendiri” ternyata berlaku pula pada Anda?
Jika memang tidak bisa membuktikan Pram membakar buku, janganlah katakan itu berkali-kali. Jika Anda hanya bisa membuktikan bahwa “Pram memberangus kebebasan berpikir” atau “mendiamkan pembakaran buku”, cukuplah Anda katakan itu saja dan tak usahlah menggunakan frase-frase berlebihan yang tak bisa dibuktikan koherensinya dengan kenyataan. Itu jauh lebih bertanggungjawab. Barangkali lebih “ilmiah”. Dan yang jelas itu jauh lebih “adil”.
Dengan terus-menerus mereproduksi frase “Pram membakari buku” pada saat sebenarnya Anda memaksudkan (dan hanya bisa membuktikan) “Pram memberangus kebebasan berpikir atau mendiamkan pembakaran buku”, Anda sama saja sedang mereproduksi jargon-jargon.
Tidak usah pula menyebut tantangan saya sebagai Agitprop seraya menulis dalam tanda kurung itu sebagai istilah PKI.
Apa pula itu maksudnya? Apakah Anda sedang mencoba membangun sebuah atribusi (diam-diam) buat saya sebagai orang yang berbahasa dengan nuansa PKI? “Tantangan berpolemik secara terbuka” tidak identik dengan Agitprop, apalagi dengan PKI. Organ-organ jaman behuela, tidak hanya PKI, biasa menggunakan istilah Agitprop, termasuk salah satu musuh besar PKI yaitu Partai Murba. Coba Anda baca Katalog Kepartaian Indonesia yang diterbitkan Kementerian Penerangan pada 1951. Janganlah mulai bikin-bikin atribusi dengan gaya stigmatisasi macam itu lah…. Biasa aja, dong!
Cara-cara Anda menyebut tantangan saya yang dinyatakan secara terbuka dengan menghubung-hubungkannya dengan “agitprop” dan “PKI” rentan membawa Anda pada laku stigmatisasi. Saya berprasangka baik Anda tidak sedang ingin membangun atribusi (diam-diam) bahwa saya “seperti PKI”, tapi cukup jelas, cara-cara macam Anda itu sering kita dengar sebelum 1998.
Jadi, Bung Arya, jika memang Anda tidak mampu membuktikan kapan dan di mana Pram membakar buku, tak usah pula Anda terus menerus mereproduksinya. Carilah parafrase/kalimat yang Anda anggap jauh lebih koheren dengan kenyataan dan yang dengan mudah pula Anda membuktikannya.
Kita tidak makin cerdas dan jernih menyikapi sejarah dengan mereproduksi terus-menerus jargon-jargon, seperti juga kita tidak bisa melawan lupa dengan cara begitu.
Orang harus membayar apa yang ia perbuat dan orang tak bisa diminta membayar apa yang tidak ia lakukan.
****
Arya,
Sekarang, mari kita omong-omong sebentar tentang buku “Prahara Budaya” yang disusun oleh DS Moeljanto dan Doktor Honoris Causa Dokter Hewan Taufiq Ismail.
Saya tidak apriori dengan “Prahara Budaya”, tapi saya tidak percaya begitu saja dengan buku “Prahara Budaya” dalam upaya memahami PKI-LEKRA-Pram.
Buku itu melulu diisi sisi keburukan PKI-LEKRA-Pram. Siapa pun yang pernah membaca buku “Prahara Budaya”, akan terjerat oleh kesan betapa ganas, bahaya, dan biadabnya PKI-Lekra-Pram. Propaganda Orde Baru tentang komunisme sebagai mahluk jahat seperti satu partitur dengan buku “Prahara Budaya”. Tidak berlebihan jika saya bilang buku itu disusun dengan cara propaganda, bukan dengan semangat ilmiah untuk menemukan “kebenaran”.
Jika ada orang yang bertanya pada saya buku apa yang berhasil membangun kesan betapa ganas dan berbahayanya Lekra-PKI-Pram, salah satu yang akan dengan tangkas saya sebutkan adalah buku “Prahara Budaya”.
Itu pula yang saya alami ketika membaca “Prahara Budaya” di awal-awal masa kuliah dulu. Kesan saya ketika itu, betapa jahat dan sama sekali tak ada nilai positifnya PKI-Lekra-Pram. Saya yang dibesarkan dalam kultur bahasa Indonesia yang baik dan benar ala Orde Baru, terperangah membaca artikel-artikel dari para pendukung PKI atau Lekra yang menggunakan gaya bahasa provokatif dan “gila-gilan”.
(Jadinya, saya pun tidak heran jika Arya Gunawan – yang juga dibesarkan dalam kultur pendidikan yang memuja bahasa Indonesia yang baik dan benar -- menanggapi subjek postingan saya yang berjudul TANTANGAN TERBUKA BUAT ARYA GUNAWAN dengan memberi komentar sebagai tulisan “bernuansa agitprov” dan pada saat yang sama masih merasa perlu menulis dalam tanda kurung “ini tentu saja istilah PKI”. Karena saya menggunakan gaya bahasa bernuansa Agitprop yang merupakan istilah PKI dan dengan demikian saya -– secara tidak langsung — dianggap “bernuansa PKI”. Bah, macam mana pula kejernihan membaca sejarah dan melawan alpa dilakukan dengan gaya pukul rata macam begini, Bung?)
Belakangan, setelah saya membacai langsung koran Harian Rakyat (milik PKI), Bintang Timur (yang lembar budayanya, Lentera, dipegang oleh Pram), Abadi (milik Masjumi) atau Duta Masjarakat (milik NU) apalagi Indonesia Raja pimpinan Mochtar Loebis, saya baru sadar bahwa gaya bahasa macam itu memang menjadi “cara wicara” (type of speech) ketika itu. Gaya bahasa macam itu memang mencerminkan dengan baik semangat zaman ketika itu yang dipenuhi semangat berpolemik, tantang menantang, hantam menghantam.
Doktor Honoris Causa Dokter Hewan Taufiq Ismail dengan baik sekali membangun kesan bahwa bahasa itu sebagai cermin kepribadian ganas PKI-Lekra, yang ia sebut sebagai gaya bahasa “caci-maki” dan “propaganda”, tetapi pada saat yang sama Doktor Honoris Causa Dokter Hewan Taufiq Ismail juga menggunakan gaya bahasa yang tidak kalah agitatifnya, seperti “mesin penyerangan untuk Manikebu”, dll.
Doktor Honoris Causa Dokter Hewan Taufiq Ismail tidak pernah menyebut-nyebut bahwa jika pun harus dicari orang yang dimintai pertanggungjawaban atas gaya bahasa yang agresif dan agitatif itu, Soekarno tidak bisa tidak tersangkut-paut dalam perkara ini. Soekarno adalah orang yang punya kemampuan membentuk “cara-wicara” dan gaya bahasa. “Prahara Budaya” tak pernah menjelaskan konteks ini secara jernih.
Arya benar bahwa “Prahara Budaya” memuat tulisan-tulisan langsung para pelaku sejarah ketika itu. Tapi, keberadaan tulisan para pelaku sejarah, tidak serta merta membuat “Prahara Budaya” menjadi cukup berwibawa untuk dijadikan rujukan memahami sepakterjang PKI-Lekra-Pram secara utuh dan proporsional.
Sebabnya, “Prahara Budaya” hanya memajang tulisan-tulisan para pelaku sejarah ketika itu dengan penyuntingan yang tidak begitu jelas teknik dan metodenya. Sementara pada saat yang sama, Doktor Honoris Causa Dokter Hewan Taufiq Ismail dan DS Moeljanto bisa dengan leluasa menuliskan kesimpulan, tafsir, dan pernyataan-pernyataan apa pun yang ingin ia suarakan.
Ini kentara, saya contohkan salah satunya, pada pengantar dia pada bagian kelima “Prahara Budaya” yang ia upayakan untuk bisa mencitrakan betapa para penyair Lekra memang menghamba pada Lenin dan Komunisme dan bahkan dianggap sudah tahu peristiwa 1 Oktober 1965.
Dia menyebut puisi penyair Mawie yang berjudul “Kutunggu Bumi Memerah Darah” yang dimuat pada Maret 1965 sebagai bukti (saya kutipkan tulisan Doktor Honoris Causa Dokter Hewan Taufiq Ismail) “karena rupanya dia sudah tahu sebelumnya”. Maksudnya, penyair Mawie dianggap sudah tahu bahwa akan terjadi pertumpahan darah pada 1 Oktober 1965.
Ini propaganda, saya kira, karena terlalu berlebihan menyebut Mawie tahu akan terjadi pertumpahan darah pada 1 Oktober 1965, apalagi Doktor Honoris Causa Dokter Hewan Taufiq Ismail tidak pernah menjelaskan argumen atas tuduhannya itu dalam sebiji kalimat pun. Dengan memvonis penyair Mawie sudah tahu peristiwa 1 Oktober 1965 jauh-jauh hari sebelumnya, kita dikesankan untuk percaya bahwa mereka semua memang terlibat, atau setidaknya, tahu.
Jika saja Doktor Honoris Causa Dokter Hewan Taufiq Ismail mau adil, dia harus katakan bahwa puisi dengan nuansa “merah-darah” tidak ada hubungannya dengan peristiwa 1 Oktober karena para penyair yang bersimpati dengan Lekra sudah terbiasa menggunakan metafora macam itu bertahun-tahun jauh sebelum 1965.
Itu bisa dibaca dari puisi Njoto berjudul “Merah Kesumba” yang diterbitkan pada Maret 1961 atau puisi Roemandung berjudul “Darah Merah di Wadjah Duka” yang ditulis di Pematangsiantar pada April 1958 dan diterbitkan Harian Rakjat pada 7 Juli 1962.
Sayangnya ini tak dimuat oleh Doktor Honoris Causa Dokter Hewan Taufiq Ismail di “Prahara Budaya”. Bukankah menggelikan jika mereka disebut tahu bahwa beberapa tahun ke depan akan terjadi peristiwa 1 Oktober 1965.
Saya dulu percaya bahwa setiap orang-orang Lekra memang terlibat dalam peristiwa 1 Oktober 1965, ya karena buku “Prahara Budaya” ini. Untung saja saya punya kesempatan untuk menelusuri sumber-sumber asli koran-koran pada zaman itu dan lebih teliti serta berhati-hati memamah “Prahara Budaya”.
Bagaimana dengan orang-orang yang tak punya akses pada sumber-sumber itu? Kasihan sekali jika mereka percaya bahwa para Mawie dan para penyair Lekra sudah tahu jauh-jauh hari peristiwa berdarah 1 Oktober 1965.
“Prahara Budaya” tidak cukup adil memberi tempat dan menggambarkan PKI-Lekra-Pram. Doktor Honoris Causa Dokter Hewan Taufiq Ismail dan DS Moeljanto hanya memajang tulisan-tulisan yang menggambarkan wajah seram PKI-Lekra-Pram dan menggiring pembaca untuk sampai pada kesimpulan itu dengan menerakan komentar-komentarnya sendiri.
Hanya dengan membaca “Prahara Budaya”, kita hanya akan mendapat cerita keganasan PKI yang menggerebek mesjid di Kanigoro tanpa akan pernah tahu bahwa PKI yang sama pernah membangun dan merehab belasan mesjid di Sumatera pada 1964. Hanya dengan membaca “Prahara Budaya”, kita hanya akan mendapat gambaran PKI-Lekra-Pram sebagai subyek-subyek yang membakari buku dan memberangus kebebasan berpikir orang-orang Manikebu (dalam istilah Pram) atau Manifestan (dalam istilah Wiratmo Soekito).
Hanya dengan membaca “Prahara Budaya”, kita tidak akan pernah menyadari satu hal penting: bahwa PKI-Lekra-Pram juga sepaham dengan Doktor Honoris Causa Dokter Hewan Taufiq Ismail dalam soal moralitas.
Belakangan saya membacai koran-koran lama, termasuk Harian Rakyat dan Bintang Timur. Salah satu hal yang baru saya sadari, dan tak akan pernah Anda sadari jika hanya membaca Prahara Budaya, adalah bahwa PKI-Lekra adalah organ yang getol sekali mengampanyekan soal moralitas, seperti juga Doktor Honoris Causa Dokter Hewan Taufiq Ismail di hari-hari belakangan.
Hanya membaca “Prahara Budaya”, kita akan kehilangan kesempatan untuk menyadari bahwa PKI-Lekra amat getol mengampanyekan anti buku-buku cabul, majalah-majalah cabul, film-film cabul, sastra cabul hingga pakaian-pakaian cabul.
Wakil CC PKI Njoto ketika pada 29 Desember 1954 naik mimbar di gedung bioskop Radjekwesi Bodjonegoro, Jawa Timur. Sebagaimana digambarkan Harian Rakjat edisi 5 Februari 1955, malam itu Njoto tak mengepit berlembar-lembar kertas pidato, sebagaimana Doktor Honoris Causa Dokter Hewan Taufiq Ismail lakukan di Taman Ismail Marzuki ketika berpidato ihwal Gerakan Syahwat Merdeka (GSM) atau pun di ruang auditorium UNY sewaktu menerima gelar Doktor Honoris Causa dalam bidang Pendidikan Sastra.
Njoto, malam itu, berbicara mengenai sikap PKI atas demoralisasi masyarakat, khususnya bagi anak-anak pelajar. Njoto bilang: “PKI menjokong setiap usaha jang akan memberantas demoralisasi, tidak sadja dikalangan peladjar, tetapi dikalangan manapun. Sekarang ini, tidak sedikit orang jang suka meremehkan pengaruh jg ditimbulkan oleh film2 tjabul, buku2 tjabul dan musik tjabul. Ibu2 dan bapak2, djuga guru2, lebih daripada saja tentu tahu betapa merusaknja barang2 tjabul itu bagi watak dan sifat anak2 kita. Pengaruh jang djelek itu sudah demikian meluasnja, sehingga tidak sedikit anak2 kita jang menanggalkan pakaiannja jg nasional, pakaiannya jang normal, dan lebih suka memakai tjelana jang saja sebut sadja ,,tjelana potlot”.”
Dalam usaha membendung keganasan “barang2 tjabul” itu PKI jauh lebih keras tindakannya. Njoto dalam pidato yang sama tak lupa berjanji merencanakan suatu mosi menuntut pelarangan segala sesuatu yang cabul kepada Parlemen. Ikatan Pemuda Pelajar Indonesia (IPPI) lantas memfasilitasi sarasehan besar “Demoralisasi Peladjar” yang digelar selama sepekan pada 27 Februari s/d 5 Maret 1955 di Jogjakarta.
Lekra cabang Jogja pernah membuat program melakukan sweeping atas pemakai baju-baju norak nekolim atau you-can-see. Bagi PKI dan eksponen Lekra, pakaian-pakaian cabul semacam you-can-see dan bikini, film cabul, sastra cabul, maupun majalah cabul bukan soal sepele. Ia adalah bagian dari arus revolusi kebudayaan yang mesti dibersihkan dari perikehidupan masyarakat.
Dan mereka konsisten dengan sikap penentangan itu. Ada sekira sepuluh tahun rentang antara pidato Njoto dan tindakan Panglima Daerah Angkatan Kepolisian X Jawa Timur di Surabaya, Drs Soemarsono, yang menyerukan bahwa “disamping terhadap lagu2 ngak-ngik-ngok sebangsa the beatle, rok n roll, AKRI akan mengambil tindakan tegas terhadap mode2 pakaian jang berbau nekolim”.
Pada 8 Juli 1961, Harian Rakjat bersikap keras terhadap film-film Amerika yang dianggap dipenuhi adegan mesum, seks dan mengajarkan kekerasan. Tulisan yang secara jelas menerangkan sikap PKI dalam hal tulisan dan tayangan seks dan kekerasan itu terpajang manis dalam judul “Hanja Menghendaki Sex dan Kekerasan”.
Majalah-majalah yang dianggap cabul seperti Playboy dirazia yang dalam bahasa kartun Harian Rakjat edisi 8 Agustus 1965 merupakan sampah-sampah berbau Amerika yang sepantasnya dibuang. Sejalan dengan itu, Badan Kontak Organisasi Wanita Indonesia Djawa Timur (BKOWI) di Surabaya juga mengeluarkan pernyataan menertibkan peredaran buku-buku dan majalah yang tak sesuai dengan kepribadian nasional. Keluarnya pernyataan itu merupakan respons langsung dari beredarnya kisah-kisah bergambar saru nan mesum yang tak pantas dilihat, “Keluarga Miring” No 8, 9, 10 terbitan Semarang tahun 1965.
Standar moral PKI, dalam hal beginian, relatif keras. Soedjojono, pelukis yang oleh Claire H0lt dalam studinya tentang sejarah seni di Indonesia maupun dalam disertasi Farida Soemargono di Ecolo des Hautes Estudes en Scien Sociales (Paris) disebut sebagai penubuh gagasan realisme (sosialis) Indonesia dalam seni rupa Indonesia ketika ia bergelut di Jogjakarta pada akhir 1930-an hingga awal 1950-an (kurang lebih seperti posisi Pram sebagai penganjur realisme sosialisme dalam kesusastraan), sampai harus dipecat karena menolak meminta maaf dan ampun setelah ia berpoligami dengan menikahi istri mudanya yang bernama Rose Pandanwangi (sama bukan dengan Partai Bulan Bintang yang berazas Islam ketika memecat Zaenal Maarif gara-gara berpoligami?). Sikap Aidit tergolong keras dalam perkara moral macam beginian.
Apakah pernah Doktor Honoris Causa Dokter Hewan Taufiq Ismail mengakui “sumbangan” PKI-Lekra dalam perkara beginian? Apakah ada pengungkapan wajah lain PKI-Lekra dalam perkara beginian dalam buku “Prahara Budaya”?
Apakah Doktor Honoris Causa Dokter Hewan Taufiq Ismail kesulitan menemukan klping-kliping seperti itu? Saya pastikan tidak mungkin.
Jika Doktor Honoris Causa Dokter Hewan Taufiq Ismail dengan mudah menampilkan kliping-kliping tulisan yang dengan telanjang menganjurkan pengganjangan terhadap Menikebu, jika mau dia juga bisa dengan mudah menemukan dan menampilkan sikap moral PKI-Lekra dalam soal seks, gambar mesum, film porno dan kekerasan. Kampanye pengganjangan Manikebu sama banyaknya dengan pengganjangan bikini, playboy, film porno, buku cabul, majalah cabul (Anda akan menyadarinya jika menyambangi langsung koran-koran pada masa itu, terutama Harian Rakyat dan Bintang Timur).
Lantas kenapa yang beginian tidak diberi tempat dalam “Prahara Budaya”? Bagi saya, cukup jelas, “Prahara Budaya” memang diabdikan untuk menggelar kampanye untuk membangun citra yang buruk terhadap PKI-Lekra-Pram.
Apakah pernah orang-orang berpikir bahwa PKI-Lekra punya standar moral yang jelas dalam perkara kecabulan? Tidak bukan? Orang hanya tahu keburukan dan keganasan PKI-Lekra. Dan buku “Prahara Budaya”, bagi saya, adalah salah satu eksponen terpenting dari proyek besar stigmatisasi itu.
Buku “Prahara Budaya” memang tidak meyakinkan untuk menjelaskan keutuhan sepakterjang PKI-Lekra-Pram. “Prahara Budaya” baru meyakinkan dalam hal menggambarkan keburukan dan keganasan PKI-Lekra-Pram.
*****
Arya,
Saya menemukan kesejajaran sikap dan standar moral PKI-Lekra dengan polah Doktor Honoris Causa Dokter Hewan Taufiq Ismail hari-hari belakangan ini yang juga doyan betul mempropagandakan sikap anti-karya sastra cabul, novel cabul, film cabul dan majalah cabul melalui peristilahan (dengan gaya menggunakan akronim yang tidak beda dengan PKI-Lekra-Pram), macam SMS (Sastra Mazhab Syahwat), GSM (Gerakan Syahwat Merdeka) atau FAK (Fiksi Alat Kelamin).
Ketika ditanya soal penggunaan akronim-akronim macam itu, GM (dalam komentarnya atas Pernyataan Ode Kampung) berkomentar dingin: “Sepertinya akronim-akronim lagi naik daun sekarang.”
Bedanya, Doktor Honoris Causa Dokter Hewan Taufiq Ismail mengalasdasari dengan dalil-dalil kitab suci sementara PKI-Lekra mengalasdasari dirinya dengan dalil-dalil revolusi anti-Nekolim yang dimuntahkan dengan begitu bersemangat di banyak sekali kesempatan oleh Bung Karno.
Jika dulu Njoto atau Aidit atau PKI atau Lekra saling bajak-membajak dengan pemerintah c.q Soekarno untuk melakukan apa yang disebut GM sebagai “memberangus kebebasan berpikir”, itu pula yang sepertinya sedang diusahakan oleh Doktor Honoris Causa Dokter Hewan Taufiq Ismail yang datang ke Parlemen untuk meminta kurikulum 2004 yang menghilangkan kata PKI dalam peristiwa 1965 untuk dibatalkan, dalam kosa kata PKI: “diganjang”. (Untuk mengetahui keterlibatan Taufiq Ismail dalam upaya membatalkan kurikulum 2004 bisa dibaca di sini
dan di sini )
Anda bisa membaca wawancara teman sekantor saya dengan sejawaran senior Anhar Gonggong yang menguak peristiwa di mana Doktor Honoris Causa Dokter Hewan Taufiq Ismail datang ke Parlemen memohon-mohon agar buku sejarah berbasis kurikulum 2004 dilarang dari peredaran. Kata Anhar Gonggong ketika itu: “Faktanya pemerintah lebih mendengar Taufiq Ismail daripada kami para sejarawan.” (komentar Anhar Gonggong selengkapnya bisa dibaca di sini )
Dari situlah asal muasal pembakaran buku pelajaran sejarah berbasis kurikulum 2004 oleh Nur Mahmudi Ismail, orang yang pernah Anda coblos dalam Pemilihan Umum di Depok tapi belakangan Anda mengaku mencabut mandat Anda padanya.
Pembakaran buku dimulai oleh sejumlah orang, termasuk Taufiq Ismail, yang menginginkan agar buku pelajaran sejarah berbasis kurikulum 2004 dihapuskan. Mereka, termasuk juga Taufiq Ismail, mengusahakan hal itu dengan banyak cara, termasuk mendatangi parlemen. Kebetulan parlemen banyak diisi oleh orang-orang yang memang alergi dengan segala macam yang berbau PKI. Kompak sudah. Klop betul.
Maka keluarlah pelarangan buku pelajaran sejarah kurikulum 2004 oleh Kejaksaan Agung. Berdasarkan itulah Nur Mahmudi membakar buku. Setelah itu, keluarlah pernyataan sikap menolak pembakaran buku. Setelah itu, Anda mengritik pernyataan sikap itu sebagai mengandung ommision of fact karena tidak mencantumkan pembakaran buku (yang katanya) dilakukan oleh Pram, seraya pada saat yang sama menyebut terus menerus buku “Prahara Budaya” yang disusun oleh Doktor Honoris Causa Dokter Hewan Taufiq Ismail, orang yang justru rajin menuntut pelarangan buku sejarah berbasis kurikulum 2004 yang jadi prolog alias asal muasal pembakaran buku oleh Nur Mahmudi.
Bagaimana bisa kita menganjurkan untuk melawan alpa dan ommision of fact dengan merekomen buku “Prahara Budaya” yang hanya menghadirkan sisi buruk PKI-Lekra-Pram seraya pada saat yang sama menghilangkan banyak hal penting dari sisi lain PKI-Lekra-Pram?
Lagipula, buku itu disusun oleh orang yang justru rajin menuntut pelarangan buku sejarah berbasis kurikulum 2004 yang kelak menjadi pangkal pembakaran buku.
Anda jangan lupa asal muasal sengkarut kelakuan Nur Mahmudi Ismail membakari buku. Karena pelarangan buku sejarah dan pembakaran buku pelajaran sejarah itu satu paket; sebab yang kedua tak mungkin terjadi tanpa kejadian yang pertama.
Apakah Anda menyebutkan peran Sang Penyusun buku “Prahara Budaya” dalam sengkarut pelarangan buku sejarah yang akhirnya berujung pada pembakaran buku sejarah? Tidak bukan?
Jika benar tuduhan Anda bahwa Pram membiarkan atau menganjurkan pembakaran buku, hal yang sama mesti Anda jelaskan di mana posisi Doktor Honoris Causa Dokter Hewan Taufiq Ismail dalam pelarangan buku sejarah yang akhirnya berujung pada pembakaran buku.
Itu baru adil namanya.
****
Arya,
Anda, seperti juga “Prahara Budaya”, tidak salah ketika menyebut adanya pembakaran buku yang tidak bisa tidak melibatkan PKI-Lekra-Pram, langsung atau tidak, berikut selisih derajat keterlibatan dan peran mereka masing-masing.
Perpustakaan USIS di Surabaya diserbu dan dibakar jam 18.30 pada 8 Desember 1964 dan diberitakan di Harian Rakjat pada terbitan 9 Desember 1965. Sebelumnya, pada 5 Desember 1964, mereka yang menamakan dirinya Front Pemuda, menyerbu gedung USIS dan lantas membakar buku-buku milik USIS di Jakarta.
Penyerbuan dan pembakaran itu dilakukan setelah mereka menghadiri Rapat Umum Setiawakan dengan Rakyat Kongo yang menolak invasi Amerika dan Belgia ke Kongo. Peristiwa ini kemudian diberitakan sebagai headline di halaman muka Harian Rakjat pada edisi Sabtu, 5 Desember 1964.
Pada hari yang sama dengan terbitnya Harian Rakjat dengan headline itu, nyaris semua surat kabar dI Jakarta juga memberitakannya. Harian Suluh Indonesia, Warta Bhakti, Duta Masjarakat, Sinar Harapan dan Bintang Timur memberitakan peristiwa USIS dan Rapat Umum Setiakawan dengan Rakjat Kongo dengan nada simpatik, sementara Merdeka (yang dipimpin oleh BM Diah, orang yang mendirikan Badan Pendukung Soekarnoisme) dan Berita Indonesia (yang didirikan salah seorang sahabat HB Jassin, Anas Ma’ruf, yang produktif menerjemahkan karya-karya Tagore, Steinbeck hingga Kabawata) bersikap antipati dengan penyerbuan dan pembakaran USIS itu.
Bagaimana sikap Lekra?
Saya belum menemukan pernyataan resmi Lekra ihwal penyerbuan dan pembakaran buku milik USIS. Yang saya temukan adalah sikap resmi Pmpinan Pusat Lekra yang menuntut penutupan USIS. Sikap resmi Lekra itu terbaca jelas di halaman muka (persisnya di pojok atas bagian kanan) Harian Rakjat dalam judul berita: “PP Lekra Dukung Tuntutan Warta Berita: Tutup USIS dan Pusat Kebudajaan AS”.
Foto pembakaran buku macam itu tidak hanya bisa didapatkan dari buku “Prahara Budaya”. Foto yang sama bisa didapatkan pula, misalnya, pada koran-koran masa itu. Juga bisa ditemukan dalam memoar yang ditulis oleh Duta Besar Amerika pada periode itu, Marshal Green, yang berjudul “Indonesia: Crisis and Transformation 1965-1968” (yang edisi terjemahannya pernah diterbitkan oleh Grafiti).
Fakta itu terlalu telanjang untuk dilewatkan begitu saja, dan saya tidak pernah berniat menggelapkan fakta itu.
Saya tidak tahu kenapa para penandatangan pernyataan sikap menolak pembakaran buku tidak menyebutkan ini (satu misteri yang membuat kawan saya, Ikram Putra, penasaran bukan main!). Biarlah para penandatangan itu yang menjawabnya, karena saya memang tidak ikut menandatangani, kendati sikap saya jelas-jelas menolak dan melawan pembakaran buku berdasar dalih apa pun.
Tetapi, jika pun mau adil dan dengan semangat untuk membicarakan sejarah secara jernih dan proporsional, mesti dijelaskan secara fair juga posisi dan dalam skala apa keterlibatan mereka, dan tidak dengan serta merta memukul rata semuanya sebagai “para pembakar buku” seperti yang dipakai Arya dalam tiga tulisan sebelumnya, yang lantas diperbaiki frasenya ditulisan Arya yang terakhir.
Gaya pukul rata ini diadopsi dari “Prahara Budaya”. Kalau pinjam istilah anak sekarang, “Prahara Budaya” banget!
Dan juga jika mau adil, “Prahara Budaya” dan juga Doktor Honoris Causa Dokter Hewan Taufiq Ismail sebaiknya menjelaskan pula sikap moral PKI-Lekra-Pram dalam hal moralitas terhadap seks, pornografi dan kekerasan; hal ihwal yang belakangan juga digembor-gemborkan oleh Doktor Honoris Causa Dokter Hewan Taufiq Ismail. Karena itu satu paket.
Jika saja Doktor Honoris Causa Dokter Hewan Taufiq Ismail menyusun “Prahara Budaya” dengan cara seperti, misalnya, Vedi R. Hadiz dan David Bourchier ketika menyusun buku “Indonesia Politics and Society: A Reader”, saya barangkali bisa lebih menghormati “Prahara Budaya”.
Buku yang disusun oleh Vedi dan Bourchier itu berisi kliping-kliping tulisan atau artikel atau manuskrip yang dianggap bisa menggambarkan dan mewakili gagasan politik yang penting selama masa Orde Baru.
Berbeda dengan “Prahara Budaya”, buku tersebut hanya menyajikan kata pengantar panjang plus anotasi dan tidak mencampurbaurkan antara opini penyusunnya dengan bahan-bahan kliping yang ditampilkan. Pembaca bisa memilah dengan baik mana yang merupakan sikap penyusun dan mana kliping aslinya. Penyuntingan memang dilakukan, tetapi penyuntingan itu dilakukan dengan tidak banyak mengubah aslinya.
****
Arya,
Sekarang mari kita omong-omong sebentar mengenai hubungan Lekra dan PKI.
Saya mencoba mengerti jika Anda, dalam tulisan terakhir, menyebut Lekra sebagai organ PKI di bidang kebudayaan dan kesenian.
Tetapi, penyebutan Lekra sebagai organ atau alat PKI tidak sepenuhnya bisa menjelaskan bagaimana sebenarnya hubungan antara PKI-Lekra. Berhenti hanya dengan menyebut Lekra sebagai organ apalagi alat PKI, bagi saya, berpeluang menghilangkan banyak detail sejarah termasuk kompleksitas hubungan antara Lekra-PKI.
Bagi saya, detail sejarah seperti itu, mau tidak mau, mesti diikutsertakan jika kita memang ingin berbuat adil dan menyajikan sejarah secara proporsional. Detail seperti itu mesti dijelaskan jika kita ingin lolos dari jeratan ommision of fact. Berhenti dengan predikat “organ atau alat PKI” saja, bagi saya, rentan untuk terjebak pada gaya berpikir “pukul rata” yang kurang kondusif bagi upaya menebarkan pemahaman sejarah yang lebih proporsional dan koheren dengan kenyataan.
Dengan semangat mengeliminasi gaya berpikir pukul rata yang mudah membawa kita pada kubangan ommision of fact, saya mencoba membagi pengetahuan dan informasi yang saya ketahui mengenai hubungan antara Lekra dan PKI.
Semua orang tahu bahwa antara Lekra dan PKI punya hubungan yang khusus. Menjadi ommision of fact jika ada yang bilang bahwa Lekra dan PKI sama sekali tak memiliki hubungan apa pun. Kedekatan keduanya terlalu telanjang untuk dilenyapkan begitu saja.
Kedekatan antara PKI-Lekra dan kedekatan keduanya dengan Soekarno begitu jelas pada periode Demokrasi Parlementer. Unsur Soekarno ini penting karena sekuat-kuatnya PKI atau Lekra, mereka tak ada artinya tanpa Soekarno. Ketiga-tiganya sama-sama doyan mereproduksi jargon-jargon revolusioner, Manifesto Politik, Neo-kolonialisme dan imperialisme dan pada semangat pada revolusi yang dibayangkan akan mamupu membebaskan Indonesia dari feodalisme dan imperialisme.
Seperti yang ditunjukkan oleh Rex Mortiner dalam studinya tentang komunisme Indonesia pada masa Soekarno, kadang ucapan PKI, ucapan pengurus Lekra atau pun ucapan Soekarno hampir-hampir tak bisa dibedakan lagi. Faktor penting Soekarno ini tak dijelaskan dengan memadai oleh “Prahara Budaya”, seakan-akan Lekra-PKI sajalah pihak yang bertanggungjawab.
Tetapi seberapa dekat sih hubungan Lekra-PKI? Apakah sedekat antara Barisan Tani Indonesia (BTI) atau Pemuda Rakyat (PR) dengan PKI? Seberapa kuat jaring komando antara PKI dengan Lekra?
Yang saya tahu, sampai munculnya Pageblug 1965, Lekra “gagal dikomuniskan” oleh Aidit dan PKI. “Gagal dikomuniskan” di situ artinya Lekra tidak pernah menjadi organ milik PKI seperti yang Anda bilang di tulisan terakhir Anda. Hal yang sama berlaku juga pada Gerwani.
Upaya mengkomuniskan Lekra atau Gerwani biasanya dilakukan dalam kongres-kongres resmi organ-organ tersebut. Jika PKI gagal mengkomuniskan mereka secara resmi, PKI biasanya lantas membentuk sendiri organ-organ yang dia inginkan.
Karena itulah PKI akhirnya membuat Konferensi Seni dan Sastra Revolusioner (KSSR) yang akhirnya menjadi organ atau onderbouw resmi PKI. Karena Gerwani “gagal dikomunsikan”, maka PKI akhirnya membentuk organ resmi yaitu Wanita Komunis.
Lekra tidak pernah menjadi onderbouw resmi PKI sebagaimana BTI, PR, CGMI, atau SOBSI, atau kalau sekarang seperti Banser bagi PKB atau Gerakan Pemuda Ka’bah bagi PPP.
Bahwa ada orang-orang komunis di tubuh LEKRA, itu jelas dan terlalu telanjang untuk dilenyapkan. Salah satu simpul hubungan antara Lekra dan PKI paling telanjang terlihat dari keberadaan Njoto di Lekra. Njoto pula salah satu orang yang ikut menggodok pendirian Lekra.
Tetapi antara Lekra dan PKI bukannya identik. Perbedaan tajam antara keduanya bukan sekali dua muncul. Sejumlah tokoh Lekra menolak campur tangan berlebihan dari partai. Instruksi-instruksi Partai yang datang seperti sabda sangat sering menjengkelkan tokoh-tokoh kunci Lekra.
Puncak perbedaan itu ya ketika PKI berniat mengkomuniskan Lekra pada 1964. Njoto sendiri, yang pernah dijuluki Brother Number Two yang merupakan Wakil Ketua CC PKI, terlibat dalam penolakan itu. Njoto pernah bilang pada koleganya di CC PKI bahwa cukuplah dirinya saja yang ada di Lekra dan tak usah sampai mengkomuniskan Lekra.
Dalam salah satu perbincangan singkat antara Muhidin M Dahlan (rekan sekantor yang sedang meneliti koran-koran kiri di masa lalu) dan saya dengan Martin Aleida di gang menuju TIM, Martin sempat kurang lebih sempat bilang: “Seandainya PKI menang, orang-orang seperti Pram dan Njoto barangkali akan dihabisi oleh PKI.”
“Kami menolak. Saya juga menolak, karena tidak bisa, misalnya, seorang Pram diperintah menjadi merah. Begitu juga yang lain. Nggak bisa,” tegas Oey Hay Djoen, orang yang saya lihat datang pada malam terakhir kehidupan Pramoedya.
Orang-orang seperti Pram, Rivai Apin, atau Soedjojono terlalu kokoh untuk diperintah ini dan itu atau disuruh menulis dan melukis begini dan begitu. Dalam kata-kata Oey, “Mereka semua sudah harimau sebelum Lekra dibentuk.”
(Barangkali ini seperti Tan Malaka, yang kendati seorang komunis, tetapi cukup jelas ia tidak bisa diperintah semau-maunya oleh Komintern. Itulah sebabnya Hatta pernah mngeluarkan komentar yang terkenal mengenai Tan Malaka sebagai orang yang tulang punggungnya terlalu keras untuk membuatnya tunduk pada Stalin.)
Uraian yang sama bisa dibaca dalam tulisan Joebar Ajoeb berjudul “Mocopat Kebudayaan”. Joebar juga menegaskan rendah dan cairnya kendali PKI terhadap Lekra.
Jangan heran juga jika kita membaca memoar Kusni Sulang (yang sekarang menggunakan nama JJ Kusni), “Di Tengah Pergolakan: Turba Lekra di Klaten”, yang bingung bukan main kenapa penelitian kesenian yang dilakukannya kok bisa dipimpin oleh DN Aidit.
Kebingungan Kusni, pernyataan Oey dan Joebar, bisa menggambarkan bahwa hubungan PKI-Lekra tidak sesederhana dan semudah seperti antara induk-semang dengan anak-semang atau antara pimpinan dan bawahan atau antara partai dengan onderbouw resminya. Bacaan-bacaan saya itu membut saya mencoba tidak gegabah menggunakan kata-kata jargon seperti “Lekra adalah organ atau alat PKI”.
Stephen Miller, seorang sarjana dan peneliti dari Australia, penggambaran Lekra sebagai alat PKI tidak realistis karena seakan-akan ada jalur komando yang berasal langsung dari Moskow atau Peking melalui Politbiro PKI lalu diteruskan ke Pimpinan Pusat Lekra. Miller menyebutkan bahwa gaya “pukul rata” menyebut Lekra sebagai alat PKI dibangun secara sistematis dan dipertahankan dengan terus menerus oleh Orde Baru.
Keith Foulcher (”Social Commitment in Litterature and the Arts”) sendiri berkesimpulan bahwa Lekra bukanlah organ apalagi alat PKI. Foulcher menyebut Lekra memang sealiran politik dengan PKI. Sementara Saskia Wieringa (“Penghancuran Gerakan Perempuan di Indonesia”) mencoba menggambarkan kerumitan hubungan itu dengan menggunakan istilah “Keluarga Komunis”. Istilah Keluarga Komunis itu oleh Antariksa (“Tuan Tanah Kawin Muda: Hubungan Seni Rupa-Lekra”) disebut sebagai penggambaran yang lebih pas bagi hubungan-hubungan lentur daripada hubungan formal-organisatoris yang bisa diperintah semaunya.
Detail-detail seperti ini tidak akan pernah dapat kita temukan secara memadai dalam “Prahara Budaya”.
Dengan caranya yang tersamar, “Prahara Budaya” menulis PKI dan Lekra dengan cara “PKI/LEKRA”. Pilihan menggunakan tanda hubung “/” punya implikasi linguistik yang tidak sederhana karena tanda “/” bisa diartikan bahwa dua entitas yang dipisah oleh tanda “/” itu sama persis atau bahkan identik, ketimbang tanda hubung “—“ yang bagi saya relatif lebih bisa menggambarkan bagaimana PKI dan Lekra beriringan dalam sejumlah hal tapi keduanya tidak kembar identik.
PKI pernah ditulis dengan cara itu oleh Soe Hok Gie dalam studinya tentang Peristiwa Madiun 1948. Gie menulis “PKI/FDR” (Front Demokratik Rakyat). Tapi cukup jelas, FDR yang terdiri dari sejumlah partai-partai kiri pada waktu itu secara resmi memang mengabungkan diri kepada PKI yang waktu itu baru saja diambil alih oleh Musso yang baru kembali dari Sovyet. Pilihan Gie untuk menggandengkan PKI dengan FDR menjadi “PKI/FDR” bisa saya terima karena konteks dan argumennya begitu jelas dan tak mungkin saya tolak.
Saya tidak sedang membangun kampanye positif bagi Lekra, PKI, Pram. Saya hanya mencoba membagi detail yang saya ketahui dari bacaan-bacaan yang saya miliki. Karena bagi saya, membaca detail-detail seperti ini merupakan kerja yang satu paket dengan upaya kita bersama untuk melawan ommision of fact.
PKI dan Lekra dan juga Pram memang tak bisa cuci tangan dari kampanye menyingkirkan karya-karya para penulis Manikebu. “Prahara Budaya” dengan begitu bersemangat sudah mencoba menjlentrehkan soal ini.
Tetapi, tiap kali menyebutkan itu, kita mesti menambahinya dengan keterangan dalam tanda kurung sejumlah detail yang mesti diketahui supaya kita semua tidak terangsang untuk terus-menerus menggunakan gaya dan frase-frase penuh jargon yang mencerminkan gaya berpikir pukul rata.
Bagi saya, membuka diri pada detail-detail begituan memungkinkan kita untuk tidak secara enteng-entengan menggunakan gaya berpikir “pukul rata”, seperti ketika Anda menyebut tantangan terbuka saya sebagai bergaya Agitprop dan menekankan dalam tanda kurung bahwa Agitprop adalah “istilah milik PKI”, pada saat partai Murba dan partai lain sebenarnya biasa menggunakan istilah Agitprop.
Itulah sebabnya saya menantang Anda untuk berbicara secara detail mengenai apa yang oleh Anda reproduksi terus-terusan dalam 3 tulisan sebelumnya sebagai pembakaran buku yang dilakukan oleh Pram. Karena saya percaya bahwa upaya untuk lolos dari jeratan ommision of fact dan propaganda sejarah bisa dimulai, salah satunya, dengan berbicara secara detail mengenai perkara-perkara yang kontroversial. Mungkin melelahkan dan tidak semua orang mau dan punya waktu untuk berpikir dan membaca detail-detail seperti ini.
Itulah yang termuat dalam buku sejarah kurikulum 2004, yang memaparkan detail lima versi mengenai siapa sebenarnya otak peristiwa 1 Oktober 1965. Ini bagus saya kira. Sayangnya, kurikulum 2004 ini lantas dilarang menyusul desakan banyak pihak, termasuk Taufiq Ismail. Dan dari pelarangan itulah pembakaran buku menjadi dimungkinkan.
Jika saja Anda mengritik pernyataan sikap dengan menggunakan kalimat (misalnya) “kenapa pembakaran perpustakaan USIS oleh organ-organ yang berafiliasi dengan PKI” tidak dimasukkan, saya tentu tidak akan pernah menantang Anda untuk berbicara secara detail. Tapi karena tiba-tiba Anda memilih untuk “mengaburkan” kenyataan sejarah yang kaya detail itu dengan frase-frase bergaya pukul rata seperti “Pram membakari buku-buku lawan ideologisnya”, maka muncullah saya untuk menantang Anda berbicara secara detail.
Pernyataan GM bahwa penting untuk mengakui kesalahan dan meminta maaf pada kesalahan yang diperbuat, bagi saya, lebih tepat disodorkan pada mereka-mereka yang terlibat dan menjadi pelaku sejarah, entah itu GM, Taufiq Ismail, Ajip Rosidi, Kusni Sulang, Hersri Setiawan, Martin Aleida, dll. Urusan merekalah itu mau mengakui dosa, meminta maaf atau meminta ampun atau apa pun yang mereka maui. Kita juga tidak bisa memaksa.
Saya tidak ada urusan dengan itu karena tugas generasi sekarang bukan mengurusi orang-orang tua yang kadang menjengkelkan dan terus menerus mereproduksi dendam di antara mereka sendiri (seperti yang ditunjukkan oleh Ajip Rosidi ketika mengungkit-ngungkit kelakuan AS Dharta di harian Pikiran Rakyat pada saat Dharta baru saja meninggal beberapa bulan silam, yang langsung disambut dengan tulisan pelaku sejarah lainnya, Martin Aleida).
Jika Anda menyebut rekonsiliasi, saya tentu saja tidak akan ikut-ikutan karena saya tidak berkonflik dengan siapa pun. Rekonsiliasi itu ya urusan mereka yang memang berkonflik dan mungkin masih saja membawa dendam hingga masa tuanya.
Tugas generasi sekarang, barangkali saya atau Anda atau siapa pun yang memang berminat, adalah membicarakan sejarah penuh dendam dan sengkarut itu dengan cara yang jernih, membuka diri pada banyak detail, dan mau menerima tafsir lain dari yang kita percayai.
Kita tidak perlu menunggu rekonsiliasi dan saling peluk-pelukan nan mengharukan dari orang-orang tua kita itu untuk bisa mengambil sikap dan pendirian dengan cara yang jernih dan logis terhadap sengkarut ini.
****
Arya,
Saya sepakat dengan Anda dalam hal melawan alpa dan melawan ommision of fact.
Untuk perkara anti pembakaran buku dan penolakan ommision of fact, saya setuju dengan Anda tanpa perlu saya tahu apakah Anda pengagum atau pembenci Pram, apakah Anda pembaca karya-karya Pram atau bukan, apakah Anda menamai anak keduanya dengan mengadopsi nama fiksi buatan Pram atau Borges atau siapa pun. Itu semua gak penting bagi saya.
Jika Anda mengajak saya untuk terlibat dalam upaya melawan alpa dan ommision of fact, saya dengan senang hati ikut bergabung, tapi tentu saja saya tidak akan merekomendasikan “Prahara Budaya” jika saya ditanya buku apa yang bisa menjelaskan secara utuh dan proporsional peran PKI-Lekra-Pram.
Jika pun saya menyebutkan buku “Prahara Budaya”, pada saat yang sama saya akan menyebutkan buku Antariksa berjudul “Tuan Tanah Kawin Muda: Hubungan Seni Rupa-Lekra”, buku Keith Foulcher berjudul ”Social Commitment in Litterature and the Arts” atau bukunya Saskia Eleonora Wieringa yang berjudul “Penghancuran Gerakan Perempuan di Indonesia” dan tulisan-tulisan para aktivis Lekra (seperti Kusni atau Hersri Setiawan) sebagai buku-buku pembanding.
Ini bukan sikap apriori seperti yang Anda tuduhkan pada Tossi atau Coen H Pontoh atau Budi Setiyono hanya karena mereka menyarankan Anda bersikap kritis terhadap “Prahara Budaya”. Saya sampai pada sikap seperti ini terhadap “Prahara Budaya” setelah saya membacanya dan membandingkannya dengan sumber-sumber lain.
Doktor Honoris Causa Dokter Hewan Taufiq Ismail boleh-boleh saja menulis apa saja yang ia percayai dan yang ingin ia percayai. Kita tidak bisa dan tak boleh melarangnya seperti juga saya tak bisa dan tidak akan pernah melarang buku “Prahara Budaya”. Tapi saya pun boleh mengambil sikap untuk tidak memercayai begitu saja “Prahara Budaya”, satu anjuran yang sudah disampaikan oleh Budi Setiyono dan Coen H Pontoh, yang sepertinya tidak begitu Anda simak dengan baik-baik.
Tentu saja saya bisa salah. Tentu saja saya bisa meleset. Tentu saja saya bisa keliru. Salah/meleset/keliru bukan hal tabu dalam polemik, yang tabu itu justru berdusta dan menutup-nutupi apa yang kita ketahui sebagai kenyataan dan kebenaran.
Arya, semoga kita selalu diberkahi sikap adil sejak dari pikiran.
Salam hormat,
Zen Rachmat Sugito
Editor di Indonesia Boekoe (i:boekoe) dan IndexPress serta mahasiswa sejarah di Universitas Negeri Yogyakarta.

 Dari Sabang Sampai Merauke
Dari Sabang Sampai Merauke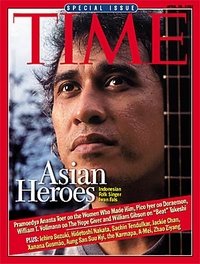 Dewa dari Leuwinanggung
Dewa dari Leuwinanggung


