Siti Nurrofiqoh
HARI SABTU, tanggal 16 Juni 2007, pukul 10.06, sudah berkumpul tujuhbelas orang di kediaman Daoed Joesoef yang terletak di daerah Kemang. Mereka adalah para peserta dan instruktur kursus Narasi Pantau, serta lima orang dari Pantau. Hadir juga Sri Soelastri, mendampingi sang suami, Daoed Joesoef.
Segera Daoed mengusulkan agar dimulai saja. Andreas Harsono, salah satu instruktur kursus Narasi Pantau segera berdiri untuk memberikan sedikit pengantar. Lalu dilanjutkan dengan perkenalan.
Andreas kemudian menjelaskan secara singkat tentang latar belakang masing-masing peserta. Ada dokter, NGO, reporter, dll. Pertemuan ini merupakan bagian dari kursus Narasi Pantau II, namun peserta kursus Narasi angkatan sebelumnya juga turut hadir.
"Masing-masing orang di sini punya proyek tersendiri untuk ditulis," ujar Andreas.
Seusai mendengar penjelasan singkat tersebut, Daoed langsung mengucapkan selamat datang bagi para peserta kelas Narasi. Pesannya yang pertama, selama proses diskusi tak ada yang boleh merokok.
Daoed lalu menjelaskan letak toilet, "Untuk ke toilet harus melewati ruang makan keluarga. Kalau dikaitkan dengan kultur di Aceh, jika tamu sudah diperbolehkan melewati ruang makan, artinya sudah bisa diterima oleh tuan rumah. Jadi kalian sudah saya terima datang ke sini."
Siang itu Daoed, yang orang Aceh, mengenakan baju lengan pendek warna krem dengan garis salur yang samar.
"Semua sudah lengkap, toh?" tanyanya.
"Sudah, Pak" jawab yang hadir secara bersamaan.
Kekayaan Indonesia, yang banyak dirongrong para pejabat, membuat Daoed merasa perlu menjelaskan lebih dulu soal rumah dan tanah yang ia tempati ini.
"Untuk menghindari adanya kemungkinan bisik-bisik di punggung," katanya.
Rumah ini didirikan di atas tanah seluas 2,000 meter persegi. Persis di depan rumahnya yang hanya dibatasi jalan selebar 2,5 meter berdiri bangunan sekolahan yang diberi nama SD Kupu-kupu. Ada halaman di sekelilingnya dan digunakan sebagai kebun yang ditanami beraneka jenis pepohonan. Di bagian dalam rumah tampak lukisan-lukisan hasil karya Daoed dan isterinya yang terpasang pada dinding-dinding ruangan.
Tanah untuk bangunan ini dibeli Daoed pada tahun 1959, ketika harga tanah masih 40 rupiah per meter.
"Jadi, ketika saya diangkat menjadi Menteri P&K pada tahun 1978, saya sudah punya rumah, tanah dan mobil. Ingat, sebelum jadi menteri lho, ya?" ujar Daoed.
"Ha…ha…ha…," tawa peserta seperti paduan suara merespon atas pernyataan Daoed.
Daoed melanjutkan, "Baiklah, dengan segala senang hati, saya ingin membagi pengetahuan yang saya sadap dari pengalaman saya menulis. Tapi sebenarnya bukan disebut pengetahuan tapi kiat."
Daoed mulai memaparkan. Menulis bukan bertujuan agar orang mempercayai kita. Tetapi supaya orang mengetahui apa yang ada dalam pikiran kita, karena pengetahuan tak ada gunanya jika hanya dibawa mati.
Daoed mengatakan dalam dua tulis-menulis hanya ada dua aturan. Aturan pertama, dunia menulis tidak punya aturan. Aturan kedua, namun dunia ini tak mengenal maaf untuk tulisan yang jelek. Setiap penulis memiliki hak untuk menggunakan ketentuannya sendiri. Kita perlu memahami bahwa sebuah buku itu mewakili kita dalam momen yang terbaik. Oleh karena itu sebagai pelukis atau penulis, orang lain tak boleh ikut campur dalam menentukan.
Hal itulah yang membedakan karya seniman dengan karya politikus. Jika karya politikus, yang belakangan diketahui ada konsep yang keliru, maka susah mengubahnya. Contoh UUD 1945, yang pada akhirnya memicu keributan saat akan diubah. Tapi kalau tulisan, kita bebas seratus persen untuk mengubahnya.
Dalam menulis kita bebas memilih kata-kata sendiri. Memilih kata-kata terkadang jadi salah satu kesulitan. Menurut Daoed, sedapat mungkin penulis jangan memakai kata-kata yang sama dalam satu halaman. Cari sinonimnya. Tak perlu khawatir karena kosa kata bahasa Indonesia kaya. Bahasa Indonesia itu feminim dan luwes. Daoed mereferensikan Tesaurus bahasa Indonesia. Menurutnya buku tersebut banyak membantu mencari kosa kata.
Hal yang menyebabkan kesulitan dalam memilih kata-kata adalah kata tersebut saat berdiri sendiri sudah baku, tapi kalau dikaitkan dengan kata yang lain, bisa jadi moderat atau mengubah makna.
"Ide di dalam pikiran kan harus kita tulis dengan kata-kata, nah.. di sinilah kadang menghasilkan konotasi yang berbeda. Itulah kenapa kita sering menyobek kertas yang kita tulis dan membuangnya ke tempat sampah," kata Daoed menuturkan pengalamannya.
"Jangan lupa bahwa sebuah tulisan punya makna sebagai karya setelah ada di tangan pembaca. Tulisan tidak bermakna apa-apa kalau masih ada di gudang penerbit atau di ruang toko buku," lanjutnya lagi.
Menyadari keragaman peserta, Daoed menyarankan bahwa dalam menulis perlu menanggalkan gelar kesarjanaan atau keilmuwanan. Dalam menulis, ilmuwan jelas berbeda dengan intelektual.
"Tanggalkan S-1 kalian. Jadilah intelektual!" tandasnya.
Hal ini dimaksudkan supaya cakupan tulisan lebih luas. Dalam bidang ilmu pengetahuan, apa yang ditulis harus eksplisit mengenai bidang tertentu. Ilmu punya bidangnya sendiri-sendiri. Sedangkan intelektual tidak. Saat orang berilmu menulis, maka ia menggambarkan suatu keadaan tertentu. Misalnya, seorang ekonom, ia hanya akan bisa mengulas soal ilmu ekonomi, meskipun pemecahan soal ekonomi ada kaitannya dengan kebijakan hukum. Tapi kalau intelektual yang menulis, maka ia akan menggambarkan keadaan secara holistik.
Seorang intelektual lebih mendekati sebagai seorang filosof. Ilmuwan mencari jawaban terhadap suatu masalah, filosof melihat masalah dalam jawaban yang sudah ada. Filosofi tidak mengenal tema khusus dalam menulis. Tapi filosof juga harus tahu diri.
"Jangan cari wisdom tapi cari kaitannya saja," Daoed berpesan.
Ada dua hal penting dalam mengajukan suatu pendapat, terutama yang menyangkut ilmu pengetahuan. Petama, correct atau benar. Kedua, applicable atau bisa diterapkan.
"
You can live without security. You can't live without assumption," ungkap Daoed.
"Menjalani hidup harus ada asumsi. Seperti Anda datang ke sini juga pasti dengan asumsi. Meski kadang apa yang sedang berjalan, lain dari asumsi pertama yang kita pikirkan. Inilah yang kadang membuat hancurnya rumah tangga," jelasnya lagi.
Setiap tulisan walaupun kadang membantah keadaan, tentu karena ada suatu maksud, yaitu membenarkan sesuatu yang sudah ada tapi tidak disadari atau membantah sesuatu yang sudah disetujui tapi ternyata keliru. Pola pikir masyarakat dibentuk oleh 4 unsur: generasi ilmiah, fakta empiris, pengertian pemikiran mitologis dan religius, serta ide politik dan etik.
EMPATPULUH ENAM menit sudah berlalu. Daoed mempersilahkan peserta bertanya sehingga diskusi yang berlangsung terbatas itu bisa sesuai dengan kebutuhan peserta.
"
Ladies first!" kata Daoed.
Nenden memulai dengan pertanyaanya. Ia ingin mengetahui lamanya Daoed Joesoef menulis buku yang berjudul
Emak. Menurut Nenden tulisan tersebut begitu detil, sehingga membuat ia merasa berada di jaman itu ketika membacanya.
Daoed menjelaskan bahwa rencana menulis
Emak sudah lama, tepatnya pada 1970-an. Sebagian tulisan itu pernah diterbitkan oleh
Suara Karya. Daoed paling ingat dengan detil masa kecilnya dan sosok emaknya, "Nanti kalau Anda tua, pasti anda akan paham. Masa kecil kita justru yang paling melekat. Apa lagi dengan orang yang sangat dekat dengan kita, yaitu emak. Tapi, bukan berarti bapak tak punya peran."
Seorang emak adalah sosok yang pasti dekat dengan anaknya. Emak digambarkan Daoed sebagai seorang perempuan yang kaya ilmu dan kebijaksanaan. Apa yang diajarkan emak, belakangan terbukti diajarkan juga di dunia kampus. Seperti tentang bagaimana cara berfikir teratur. Ilmu adalah berfikir teratur. Ketika sang emak tak dapat menjawab pertanyaan anaknya, maka anaknya diarahkan bertanya di sekolah. Emak menyadari betul pentingnya pendidikan.
Andreas menanyakan mengapa penulisan buku Emak, yang naratif, enak dibaca, berbeda dengan tulisan-tulisan terdahulu Daoed Joesoef, yang cenderung kering, bicara soal ekonomi, politik, notabene kurang luwes dan mengalir.
Menurut Daoed dikarenakan oleh sosok emak sendiri yang memang begitu adanya.
"Itulah, saya membenarkan apa kata pepatah bahwa di balik kesuksesan orang besar ada campur tangan seorang wanita. Dan wanita itu salah satunya adalah emak saya," kenangnya.
Begitu Daoed selesai menjawab pertanyaan, Hagi Hagoromo langsung menanyakan perihal penggunaan huruf besar pada nama belakang Daoed Joesoef.
Hal itu bermula setelah kepulangan Daoed dari Sorbone. Daoed yang juga suka melukis, terkadang mencantumkan nama tersebut dalam lukisannya. Nama Joesoef adalah nama sang bapak dan supaya tidak terkesan Arabik
Daoed Joesoef yang ketika masih mahasiswa suka membeli sepatu loak di Tanah Abang, terus berbicara dengan antusias. Tidak hanya soal menulis, peserta juga banyak diajak berdiskusi tentang hal-hal yang lain. Ketuhanan misalnya. Menurutnya, ketuhanan itu tidak bisa direduksi menjadi agama. Hal itu pula yang sempat disayangkan olehnya ketika jam pelajaran sekolah banyak terpakai buat pelajaran agama. Padahal agama bisa dipelajari di surau pada malam harinya. Apalagi melihat perkembangan sekarang, agama menjadi pembenaran untuk melakukan kekerasan, yang membuat Daoed merasa sengit.
Daoed juga menyayangkan sikap para mahasiswa kita yang tidak pernah punya konsep dalam berpolitik. Dalam politik itu ada dua arti, yaitu dalam artian konsep dan arena. Sebenarnya tidak dibenarkan adalah gerakan mahasiswa yang mengatasnamakan kampusnya. Tapi mahasiswa di Indonesia, lebih memilih pakai nama itu. Rakyat yang masih bodoh menganggap hal itu ilmiah. Konsep begitu penting dalam berpolitik karena orang-orang yang punya konsep akan menjadi manusia otonom, sekaligus sebagai cikal-bakal civil society.
Manusia bahagia bukan karena ia bisa membeli kekayaan, namun karena ia menjadi manusia. Kita semua diminta untuk berpikir.
"Ini sudah jam makan siang. Sudah dua jam," Andreas mengingatkan. Peserta minta diperpanjang. Daoed minta diperpanjang setengah jam.
Siti Maemunah mengajukan dua hal yang diawal pembicaraan sempat disinggung oleh Daoed. Soal pembangunan (bumi yang diabstraksi) dan tentang bahasa Indonesia yang disebut oleh Daoed sebagai bahasa feminim.
"Saya belum bisa menangkap lebih jauh soal itu, pak," katanya.
"Saya jawab yang kedua dulu ya, karena yang pertama itu sulit," kata Daoed seraya bergurau meski tanpa senyum.
"Memang ada usaha pembakuan arti dalam kosa kata yang salah satunya dilakukan oleh profesor bahasa di UI. Paul… siapa itu. Tapi kok malah jadi kaku gitu. Beda dengan bahasa melayu, meski bahasa Indonesia bukan melayu. Pembakuan belum begitu merata. Saya kira itu tidak perlu juga. Bahasa itukan hidup. Tak ada salahnya, jika kita masukkan bahasa anak muda yang menyebut bapak dengan bokap atau apalah," jelasnya kemudian.
"Ha..ha..ha…," pernyataan tersebut membuat peserta tertawa lepas.
"Bahasa itu alat komunikasi, jadi harus bisa dipahami," Daoed melengkapi.
Saat menanggapi pertanyaan Maemunah yang pertama, Daoed mengingatkan arti penting pembangunan desa pantai.
Pembangunan seringkali melupakan bahwa bumi yang kita tempati berbentuk archipelago. Terdiri atas kepulauan-kepulauan yang tersebar di dunia. Hal itu diabstraksi sehingga seolah-olah setiap pojok di negeri ini mempunyai keperluan yang sama untuk bisa dibangun. Dengan bentuk bumi seperti ini, seharusnya pembangunan disesuaikan kondisi wilayahnya.
Seharusnya kita membangun desa-desa pantai. Di sepanjang pantai dihuni oleh manusia. Meski mata pencaharian mereka di laut, tetapi mereka tetap tinggal di darat, bukan di perahu. Harusnya lingkungan pantai juga dibangun karena orang-orang yang tinggal di sana kita percayakan untuk menjaga pantai itu. Pantai yang panjangnya mencapai sepuluh kali lingkaran bumi ini merupakan pantai terpanjang didunia.
"Tidak mungkin kita menyuruh Angkatan Laut untuk menjaga pantai yang begitu panjang," ujar Daoed.
Pembangunan tidak bisa hanya didasarkan pada ilmu ekonomi atau financial cost-nya saja tapi juga oportunity cost. Hal itu tentu tidak menjadi keputusan pusat, melainkan harus dibicarakan dengan orang setempat, menyangkut kesempatan yang bakal hilang dan kesempatan yang akan diperoleh.
Sudah lebih dari dua jam Daoed mengeluarkan energinya untuk berbicara. Namun saya tak melihat ada perubahan dalam nada bicaranya. Tak ada serak atau terbatuk. Tetap lantang dan terdengar jelas hingga ke ujung ruangan yang berjarak sekitar 5 meter. Bahkan ia sendiri berpesan bahwa saya tak perlu menyediakan alat pengeras suara.
Selly Sumartini yang tampak selalu mengamati setiap gerak-gerik Daoed, ingin tahu makanan apa yang dikonsumsi keluarga itu? Dalam bayangannya ketika membaca buku Emak, pasangan Daoed dan isteri diperkirakan sudah sepuh. Tak salah duga karena dari segi umur Daoed dan istrinya masing-masing sudah mendekati usia 80 tahun.
Resep mereka masih terlihat segar adalah faktor pikiran. Bagi Daoed yang sudah harus mengurangi garam karena penyakit jantung koronernya dan Soelastri yang harus menjauhi gula, termasuk susah untuk menyantap makanan yang lezat. Bahkan sebagai orang Medan ia megisahkan merasa cukup makan dengan sambal dan ikan asin.
"Tidak selalu dalam bentuk makanan. Tapi lebih cenderung ke faktor pikiran," katanya mantap.
Menjawab Ambri Rahayu, yang bertanya soal kaitan bakat dalam menulis, Daoed berkomentar, "Bukan saya tak percaya bakat. Tapi, saya hampir tak pernah memikirkan itu. Yang penting tulislah apa yang ada di pikiran kita, lalu bacalah. Sudah enak atau belum. Setiap gagal, coba lagi. Menulis itu bisa dikembangkan, asal kita tahu untuk apa kita berbuat itu."
Entah ada hubungannya dengan soal tulisan atau tidak. Tapi Imelda, alumnus Narasi I, lebih tertarik bertanya soal apa yang membuat Soelastri jatuh cinta dengan Daoed. Pertanyaan yang membuat semua tergelak termasuk Daoed.
"Wah, malah saya belum pernah tanya itu…ayo katakan, Bu," pinta Daoed.
Ternyata hal itu memang belum pernah ditanyakan sepanjang pernikahannya. Lalu, pemuda era 1950-an itupun bersiap mendengar pemaparan pujaan hatinya, yang sudah hampir 50 tahun menjadi teman hidupnya, suka dan duka. Kedua tangannya dibiarkan menggantung di sandaran kursi. Santai namun serius.
Sesaat suasana hening. Semua menunggu Soelastri. Perlahan kalimat-kalimat lembut mulai terurai dari mulutnya. Beberapa pernyataan pun sering diulang sebagai bentuk penegasan.
"Bapak itu tak pernah basa-basi. Bapak orangnya tak pernah merayu atau memberi janji-janji kosong," ungkapnya.
"Ha..ha..ha…," Ibu sempat berhenti karena peserta menginterupsi dengan tawa yang terbahak-bahak.
"Bapak…. juga orang yang tidak hanya ngomong, tapi berbuat dan berusaha. Kerja keras. Itu yang saya hargai," pandangannya nampak menerawang.
"Kalau gantengnya gimana Bu?" tanya Andreas.
"Ada kandidat lain tidak Bu?" tanya Algooth Putranto.
"Ya bapak, ya ganteng, meski tak berarti ganteng banget. Tapi esensinya karena saya merasa ada kecocokan, tidak kosong, jujur dan bisa dipercaya. Bapak orang yang jujur dan bisa dipercaya. Kalau yang lain-lain itu hanya suka
plirak-plirik, janji-janji, itu kosong. Itu ndak saya
reken. Udah, toh," kata Soelastri.
Tirai masa lalu sudah dilipat lagi. Untuk dikemas dalam kesetiaan dan saling menghargai di sepanjang waktu mereka di dunia. Soelastri kadang mengalah untuk Daoed, dan Daoed kadang mengalah untuk Soelastri. Ada yang dipertaruhkan dan ada yang didapat. Semua pengorbanan dilakukan untuk sesuatu yang jelas dan sesuatu yang diyakini mereka. Menjaga komunikasi dan menghargai perbedaan menjadi salah satu faktor yang membuat mereka
fresh di usianya yang sudah hampir 80 tahun.

 Dari Sabang Sampai Merauke
Dari Sabang Sampai Merauke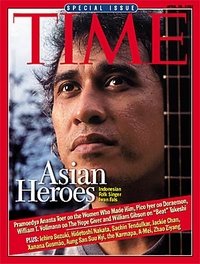 Dewa dari Leuwinanggung
Dewa dari Leuwinanggung





