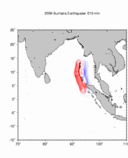Oleh WEINATA SAIRIN
Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri secara bersama menerbitkan Keputusan No. 01/Ber/MDN-MAG/1969 tanggal 13 September 1969 tentang "Pelaksanaan tugas aparatur Pemerintah dalam menjamin ketertiban dan kelancaran pelaksanaan pembangunan dan ibadat agama oleh pemeluk-pemeluknya". SKB ini diterbitkan sesudah terjadi serangkaian kasus perusakan gedung gereja antara lain di Makasar (Oktober 1967), Slipi (April 1969) dan "gagalnya" Musyawarah Antar-Agama 30 November 1967.
Wakil Protestan dan Katolik dianggap telah menyebabkan gagalnya musyawarah tersebut karena mereka menolak suatu rumusan yang telah disiapkan pemerintah di akhir musyawarah dalam bentuk piagam sehingga piagam tersebut tidak jadi dikeluarkan. Dari tiga butir pemikiran yang menjadi isi piagam tersebut, salah satu butirnya ditolak wakil Protestan dan Katolik yang berbunyi: "Saling membantu satu dengan lainnya, moril-spiritual dan materil dan berlomba-lomba untuk meyakinkan golongan atheis untuk berkepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan tidak menjadikan umat yang telah beragama sebagai sasaran penyebaran agama masing-masing" (cetak tebal dari WS).
Pelarangan penyebaran agama seperti itu bertentangan dengan hakikat agama itu sendiri apalagi agama yang bersifat misioner/dakwah seperti Kristen dan Islam.
Titik lemah
 Dalam pelaksanaan di lapangan, ternyata SKB tersebut banyak menimbulkan kesulitan, khususnya yang dialami oleh gereja-gereja di Indonesia. Titik pangkal permasalahan terutama sekali oleh karena isi Pasal 4 SKB tersebut yang tanpa Petunjuk Pelaksanaan yang jelas telah membuka kemungkinan interpretasi yang beragam yang justru makin mempersulit izin pembangunan gereja. Pasal 4 ayat (2) dan (3) menyatakan bahwa Kepala Daerah /pejabat memberikan izin setelah mempertimbangkan pendapat Kepala Perwakilan Departemen Agama setempat, planologi, kondisi dan keadaan setempat bahkan jika dianggap perlu dapat diminta pendapat dari organisasi-organisasi keagamaan dan ulama/rohaniwan setempat.
Dalam pelaksanaan di lapangan, ternyata SKB tersebut banyak menimbulkan kesulitan, khususnya yang dialami oleh gereja-gereja di Indonesia. Titik pangkal permasalahan terutama sekali oleh karena isi Pasal 4 SKB tersebut yang tanpa Petunjuk Pelaksanaan yang jelas telah membuka kemungkinan interpretasi yang beragam yang justru makin mempersulit izin pembangunan gereja. Pasal 4 ayat (2) dan (3) menyatakan bahwa Kepala Daerah /pejabat memberikan izin setelah mempertimbangkan pendapat Kepala Perwakilan Departemen Agama setempat, planologi, kondisi dan keadaan setempat bahkan jika dianggap perlu dapat diminta pendapat dari organisasi-organisasi keagamaan dan ulama/rohaniwan setempat.Dari pengalaman konkret, sulit sekali pejabat memberikan izin oleh karena berbagai hal:
a) Pejabat yang berwenang acapkali tidak mampu memerankan diri sebagai pejabat pemerintah dengan visi kenegaraan yang memadai sehingga bersedia mengayomi warga negara serta membantu perizinan pembangunan rumah ibadah; tapi lebih berfungsi sebagai pejabat yang beragama tertentu dan sebab itu memihak kepada suatu kelompok agama tertentu.
Pejabat yang berwenang acapkali tidak berani/mampu bersikap objektif dan bertindak sebagai pejabat yang arif dalam hal pemberian izin, namun sikapnya amat ditentukan oleh sejumlah tanda tangan dari perorangan/organisasi yang digunakan sebagai syarat untuk memperoleh izin, dan yang sering terjadi adalah masyarakat sekitar menolak pembangunan rumah ibadah (gereja), walaupun mereka tinggal jauh dari tempat pembangunan gedung gereja.
b) Pejabat setempat sering membuat persyaratan lokal (jumlah pemeluk agama, radius dari rumah ibadah agama lain, jumlah rumah ibadah sejenis yang telah ada), yang lebih berat dari isi SKB itu sendiri.
- Instruksi Gubernur Jabar, No. 28 Tahun 1990 menetapkan antara lain plafon 40 KK untuk bisa memperoleh izin pembangunan.
- Keputusan Walikota Kodya Palembang No. 11/1990 antara lain mensyaratkan penelitian lapangan bagi pejabat pemda untuk mengecek apakah di lokasi pembangunan ada tempat peribadatan lain, atau tempat peribadatan sejenis, fasilitas hiburan.
Mengingat sulitnya mendapat izin pembangunan gedung gereja, warga gereja menyelenggarakan ibadah di rumah tinggal, di ruko serta di hotel-hotel. Penggunaan rumah tinggal yang difungsikan sebagai gereja oleh beberapa jemaat Kristen, telah memicu ketegangan hubungan antar-umat beragama bahkan dalam suatu kasus pernah menjurus kebentrokan fisik.
Sebab itu Mendagri dalam Surat Kawat No. 264/KWT/DITPUM/DV/1975 menyatakan agar rumah tinggal tidak difungsikan sebagai gereja. Namun oleh karena ada kesalahan interpretasi terhadap isi Surat Kawat itu maka pernyataan itu ditegaskan lagi melalui Surat Kawat No. 933/KWT/SOSPOL/DV/XI/1975 yang menyatakan bahwa "yang berkumpulnya orang Kristen/Katolik dalam satu rumah tinggal sedangkan berkumpulnya orang Kristen/Katolik dalam satu rumah dengan kegiatan kekeluargaan tidak pernah dilarang."
Berkaitan dengan kesulitan pembangunan rumah ibadah PGI berulang kali dalam berbagai kesempatan meminta kepada pemerintah agar kondisi seperi itu tidak terjadi dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila sebagai penegasan Memorandum tanggal 10 Oktober 1969. Adalah hal yang menggembirakan jika para pejabat pemerintah mengungkapkan concern yang serius terhadap pergumulan yang disampaikan oleh PGI. Hal itu tercermin antara lain melalui surat Menteri Menkopolkam No. R34/MENKO/POLKAM/6/1992 tanggal 9 Juni 1992; dan ceramah Menko Polkam Sudomo dalam Sidang MPH PGI tanggal 26 November 1991.
Beberapa titik lemah yang amat signifikan dari SKB Menag-Mendagri 1969 adalah:
a) Ketentuan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum karena SKB tidak termasuk dalam Tata Urutan Peraturan Perundangan RI (TAP MPR No. III/MPR/2000).
b) Ketentuan tersebut bertolak belakang bahkan menyeleweng dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 walaupun dalam konsiderans SKB tersebut menyebut Pasal 29 UUD 1945.
c) Penyebaran agama dan pelaksanaan ibadah agama diturunkan/direndahkan derajatnya menjadi kewenangan kepala daerah untuk mengaturnya, membimbing dan mengawasinya sehingga penyebaran tersebut tidak menganggu Ketertiban Umum (Pasal 1,2).
d) Peranan pemerintah/Kepala Perwakilan Departemen Agama amat besar bahkan cenderung dapat mengintervensi khotbah di rumah-rumah ibadah sebagai suatu kegiatan sekuler yang mesti diawasi Pemerintah demi terwujudnya stabilitas keamanan.
e) Pendirian/pebangunan rumah ibadah tidak dipahami sebagai pembangunan sebuah gedung yang tingkat kerawanannya amat tinggi sehingga membutuhkan "rekomendasi" dari berbagai pihak (Pasal 4).
Hal yang amat mendasar di sini adalah munculnya interpretasi seolah pembangunan rumah ibadat itu amat tergantung pada rekomendasi/persetujuan/belas kasihan seorang pejabat atau suatu kelompok golongan tertentu. Arogansi birokrasi dan arogansi mayoritas pemeluk agama bisa terjadi di sini. Kondisi ini bertentangan secara diametral dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
Pemerintah menyadari adanya banyak kelemahan dari SKB tersebut, sebab itu pada tahun 1992, Depdagri melakukan penelitian di lima wilayah: DKI Jakarta, Kodya Pontianak, Kodya Palembang, Kodya Surabaya, Provinsi Jabar.
Berdasarkan evaluasi itu, Departemen Dalam Negeri pada tanggal 15 Maret 1993, 23 Maret 1994 mengundang PGI bersama dengan lembaga-lembaga keagamaan lain dalam rangka membahas Rancangan Mendagri tentang Pendirian Rumah Ibadat. Rancangan yang berisi 16 pasal itu ingin mengatur tentang izin pembangunan rumah ibadat sebagai pengganti SKB 1969. Terhadap Rancangan itu PGI memberikan usul perubahan antara lain agar Rancangan itu harus mengacu kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, agar pemberian keterangan tertulis dari pejabat tidak didasarkan pada jumlah riil penganut agama di suatu wilayah, tetapi pada urgensi karena ada banyak denominasi di sesuatu wilayah dan anggota jemaat tidak hanya berdomisili di sekitar rumah ibadat yang akan dibangun; pelaksanaan ibadah tetap berlangsung sambil menunggu izin keluar; kepala daerah agar meminta pertimbangan organisasi keagamaan dari umat beragama yang sedang membangun rumah ibadah. Hingga saat terakhir Rancangan tersebut tidak terdengar lagi.
Arah ke depan Dalam suasana reformasi yang menuntut perubahan paradigma segala bentuk ketentuan perundangan berbagai aras yang diskriminatif perlu diganti.
SKB Menag-Mendagri 1969 amat merugikan semua agama di Indonesia, terutama sekali gereja-gereja telah mengalami penderitaan yang amat dalam sehubungan dengan SKB tersebut. Secara hukum, konstitusional, material, teologis, SKB itu amat kontraproduktif dan diskriminatif.
Tak ada pilihan lain kecuali pemerintah mencabutnya dan mengupayakan agar ada penyamaan izin pembangunan rumah ibadah dengan izin bangunan-bangunan yang lain. Penyusunan suatu ketentuan baru tentang pembangunan rumah ibadah harus menjadikan hal berikut sebagai referensi utama:
a) Ketentuan tersebut harus berangkat dari kondisi realistik bahwa masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang menganut berbagai agama, dana agama-agama itu mempunyai hak serta kewajiban yang sama dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan tidak boleh diperlakukan dengan bertolak dari jumlah penganut.
b) Ketentuan tersebut harus mengacu serta mencerminkan jiwa dan semangat Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, GBHN, Wawasan Nusantara yang memberi posisi sentral bagi kehidupan keagamaan masyarakat Indonesia dan yang di dalamnya kemerdekaan tiap penduduk untuk memeluk agamanya dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya dijamin oleh negara.
c) Ketentuan tersebut harus memberi peluang bagi penambahan sarana-sarana rumah ibadah sebagai bagian padu dari pembinaan mental-spiritual.
d) Ketentuan tersebut memberikan penegasan tentang peranan negara (sesuai dengan Pasal 29 ayat 2 UUD 1945) sehingga pembangunan rumah ibadah tidak seakan-akan tergantung dan atau merupakan belas kasihan dari seorang pejabat atau suatu kelompok/golongan tertentu di dalam masyarakat.
d) Ketentuan tersebut tidak boleh membatasi/menghalangi hak setiap makhluk untuk mengekspresikan keberagamaannya kepada Sang Khalik. Artinya jika oleh karena satu dan hal, rumah-rumah ibadah belum dapat dibangun, maka hak umat beragama untuk mengungkapkan keberagamaannya kepada Allah Yang Esa itu tetap dijamin, walaupun untuk sementara tidak dilaksanakan di dalam ruang gereja/ ruang ibadah yang khusus.
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wapres M. Jusuf Kalla bersama Kabinet Indonesia Bersatu mesti memberi perhatian serius terhadap realitas ini!
Penulis adalah teolog, pengamat masalah sosial keagamaan.